JAKARTA sore ini berisik seperti biasa. Knalpot, teriakan pedagang kaki lima, dan suara klakson bersahut-sahutan, seolah tak peduli pada hati yang sedang gentar. Aku duduk di pinggir jalan, tepat di bawah pohon ketapang yang tak terlalu rindang. Kemeja lamaku sudah tak serapi pagi tadi. Keringat, debu, sudah berteman akrab. Bahkan rambut yang sudah ku tata rapi kini berantakan kesana kemari, cerminan hatiku yang tak kalah semrawut. Aku menghela nafas lelah, seraya meneguk air dari botol minum yang sedikit keriput dan peyot, entah beberapa kali sudah aku genggam. Hiruk pikuk Jakarta seakan hanya angin lewat, pikiranku kalut tentang pekerjaan yang tak kunjung menjemput. Aku terus mengecek ponsel ku, berharap ada sesuatu yang membuat hati semula gundah gulana menjadi sorak gembira.Nyatanya nihil, hanya layar kosong yang menatap balik. Wajahku yang kucel memantul, kusam disapu debu Jakarta. Rasanya seperti menggenggam angin—kosong, tak berarti, tersisa rasa dingin di sela-sela jari.Aku merogoh saku, berharap menemukan harta karun di dalam sana. Tetapi kenyataan selalu pahit, hanya tersisa uang dua ribu rupiah yang lecek, ditemani koin lima ratus rupiah yang berwarna keabu-abuan. Senyum pias terbentuk di wajahku, sepertinya harus benar-benar berhemat minggu ini. Tiba-tiba ponselku bergetar, memberi tanda ada panggilan masuk. Aku buru-buru melihat siapa yang menelpon, berharap itu orang dari kantor tempat aku melamar. Senyum ku merekah, tetapi perlahan memudar digantikan tatapan sinis karena ternyata bukan orang kantor atau semacam itu, melainkan teman ku, seperjuangan, konco kentel katanya. “Ngapain telepon kalau dekat, Bim!” Aku mengomel karena ternyata pelaku hanya berjarak beberapa meter dari tempat yang sedang aku duduki, sedang senyam-senyum tak jelas. Tangan ia masukkan ke saku, dan tidak lupa rambutnya yang seperti tidak pernah ia tata atau sisir. Dengan jaket lusuh yang jadi andalannya, dan ransel kecil yang entah apa isinya, Bima datang menghampiri ku. Langkahnya tampak menjengkelkan, wajahnya seperti mengejek ke arahku yang sedang mumet. Kendati aku tahu itu hanya efek suasana hati ku yang sedang kacau. “Ndre, mangan sek disik. Biar ra tambah mumet,” Bima tertawa kecil, menggeleng pelan sembari duduk di sampingku. Logat Jawanya sangat kental, mengingat dia memang orang asli Pemalang, Jawa Tengah. Aku hanya mengangguk, tidak ada tenaga untuk berdebat. Perutku memang lapar, tapi lebih lapar lagi hatiku akan kepastian. Lamaran kerja sudah kukirim ke mana-mana. Wawancara datang, tapi hasilnya selalu sama—“kami akan hubungi kembali.” Tapi hingga kini, tak satu pun yang benar-benar kembali, menyebalkan! Bima duduk di sebelahku. Kakinya selonjor, dan dia membuka bekal nasi bungkus dari warung dekat kos. “Rejeki gak bakal kemana, Andre,” ujarnya sambil menyodorkan setengah bungkus nasi goreng padaku. Aku menerimanya sedikit tergesa-gesa, kelihatan sekali aku memang kelaparan. Bahkan nasi goreng biasa tampak seperti nasi goreng hotel bintang lima. Oke, ini berlebihan. Kadang aku iri pada Bima. Meski hidupnya sederhana, dia selalu tampak kuat. Dia cuma kerja di bengkel temannya, upahnya harian, dan menurutku tak seberapa. Tapi dia selalu bilang, ‘Iki luwih dari cukup lho, Ndre.’ Aku hanya bisa cengengesan saat mendengarnya, bingung dengan sikap yang santai itu, seperti tidak ada beban. Aku memang sempat ditawari untuk bekerja di bengkel punya temannya, tetapi aku langsung menolak, aku merasa itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi jika aku harus mengirim uang ke kampung untuk biaya kehidupan orang tua beserta adik ku yang masih menginjak bangku SMP. Bukannya menolak rezeki, aku hanya bersikap realistis. Gaji bekerja di bengkel tentu tidak cukup untuk membiayai semua kebutuhan yang harus kutanggung. Mungkin cukup jika hanya untukku sendiri, tapi jangan lupa, ada banyak angka yang perlu kupikirkan matang-matang. Maka dari itu, aku terus melamar ke sana ke mari, berharap ada pintu yang terbuka. Pernah suatu kali aku pulang dari wawancara dengan senyum lebar. Pewawancaranya menepuk bahuku dan berkata, ‘Kami suka semangatmu.’ Aku kira itu pertanda baik, mungkin titik balikku. Harapan sempat tumbuh, membuatku percaya bahwa usahaku akan berbuah. Tapi… hari-hari berlalu, dan tak satu pun kabar datang. Kini, melihat Bima yang tetap tersenyum meski hidupnya pas-pasan, aku merasa cemburu. Kenapa dia bisa sebahagia itu, sementara aku merasa terus dihantam kecewa? “Belum di terima tah, Ndre?" Sekelumit pertanyaan singkat itu mampu membuatku terdiam, menghela nafas pelan. Mulut yang tadinya sibuk mengunyah tiba-tiba berhenti, digantikan raut wajah yang sunyi. Aku mengangguk kecil, mengiyakan pertanyaan itu. “Belum, Maem,” jawabku lirih, nyaris tenggelam di tengah hiruk-pikuk kota. Bima tidak langsung menjawab. Dia cuma manggut-manggut, lalu menepuk pundakku dengan gaya khasnya yang seperti bapak-bapak bijak dari Pemalang. “Ndre… jangan menyerah. Kamu ngerti, rejeki itu ora mung soal cepet-cepetan. Kadang kudu ngaso dulu, ngopi sek, baru lanjut lari maneh.” Aku tersenyum kecut, setengah ingin ketawa, setengah lagi ingin rebahan permanen. Nasi yang tersisa itu terus aku aduk pelan, seolah enggan ku telan. Jari-jariku bergerak tak tentu arah, membentuk pola di piring seperti seorang anak kecil yang iseng membuat kerajinan tangan— mungkin kita bisa menyebutnya ‘kerajinan tangan nasi goreng sisa’. Entah kenapa, ada ironi yang mengendap di sana: sisa-sisa nasi itu seolah melambangkan hidupku sendiri, berserakan, tak utuh, seperti serpihan harapan yang coba kususun kembali, meski tak selalu membentuk sesuatu yang utuh. “Kadang aku iri sama kamu, Bim,” gumamku tanpa menoleh. Bima menoleh, terkekeh geli, “Iri apa? Aku wae kerja kucel, tangan belepotan oli tiap hari.” Aku mendesah, “Justru itu. Kamu sederhana… tapi kamu kayak tenang. Aku? Nyari kerja udah kayak nyari jodoh—dilihat doang, tapi nggak pernah dipilih.” Bima ketawa mendengar keluhan yang dibumbui lelucon itu, “Ndre… kamu tuh kadang terlalu mikir tinggi. Coba deh lihat itu,” ujarnya sambil menunjuk ke seberang jalan. Aku menoleh. Di seberang jalan, seorang bocah berdiri di bawah temaram lampu merah. Tangannya kecil, menggenggam beberapa bungkus tisu lusuh. Tubuhnya ringkih, sandal sebelahnya hampir putus, dan jaket tipisnya tak cukup untuk menepis dingin malam. Tapi matanya... matanya tak kalah tajam dari para pencari harapan. “Masih mending kamu bisa makan nasi goreng, topping ayam pula. Lha bocah itu? Urip wae kudu ngadu nyali. Bukan soal diterima kerja atau nggak, tapi soal bisa makan atau tidur dengan perut kosong malam ini.” Aku tercekat. Suap terakhir nasi goreng itu mendadak terasa pahit di mulutku. Perutku kenyang, tapi dadaku kosong, kosong oleh rasa malu, oleh kenyataan bahwa perjuanganku selama ini tak seberat langkah kecil bocah itu. Peluh menetes dari pelipisnya yang kecil dan kotor, mengalir bersama butiran debu dan lelah yang tak pernah hilang. Senyum kecil itu tetap ia layangkan, meski wajahnya letih, saat menawarkan tisu kepada pengendara yang bahkan enggan menurunkan kaca. Dia tak mengeluh, tak bersuara, tapi tatapannya seperti menembus langsung ke relung hatiku yang paling dalam. Seolah berkata tanpa kata:“Kau lelah mengejar impian dan cita-cita, sementara aku? Aku hanya berjuang untuk bertahan, bertahan agar besok masih ada kesempatan untuk hidup.” Aku terpaku. Tubuhku membeku, dan dadaku seperti ditekan batu yang berat. Diamku bukan karena aku tak tahu harus berkata apa, tapi karena kata-kata terasa tak cukup, tak mampu mengungkapkan rasa malu dan haru yang membuncah. Hatiku tertunduk, bertekuk oleh kenyataan yang selama ini aku hindari. Aku yang merasa telah berjuang keras, ternyata masih jauh dari arti sebenarnya perjuangan. Aku masih jauh dari kata kalah, tapi juga sadar bahwa aku belum benar-benar menang. Malam itu, di bawah kerlip lampu jalan, pelajaran hidup yang paling tulus datang dari tangan mungil dan senyum sederhana seorang bocah kecil yang menjajakan tisu. “Kadang kita cuma butuh diingetin, ya, Bim…” ucapku, setengah berbisik. Bima hanya nyengir, lalu menepuk pundakku. “Urip ki ora kudu langsung mentereng, Ndre. Yang penting terus maju, inget sama Gusti Allah.” Aku tak langsung menjawab. Hanya terdiam, menatap nasi goreng yang tinggal sisa, kemudian pelan-pelan mengangguk. Senyum tipis muncul tanpa sadar di wajahku—bukan karena semua masalahku selesai, tetapi perlahan aku mengerti, masih banyak orang lain di luar sana yang memikul beban jauh lebih berat dariku. Kami pun tertawa kecil bersama. Ringan, seadanya, seperti dua sahabat yang sedang mengolok nasib tapi tetap memilih bertahan. Angin malam mulai menyapa pelan, membawa suara adzan Maghrib dari kejauhan. “Maghrib, Ndre. Sholat sek, yuk.” ajak Bima sambil berdiri. Aku mengangguk. “Iya, Bim. Mungkin itu yang aku lupa selama ini…” Kami pun berjalan beriringan menuju masjid kecil di ujung jalan, meninggalkan sisa nasi goreng yang dingin, juga percakapan panjang yang belum tentu ada jawabannya. Langit mulai menggelap, entah kenapa hati terasa sedikit lebih ringan. Mungkin bukan karena solusi, tapi karena aku tahu bahwa aku tidak sendiri.
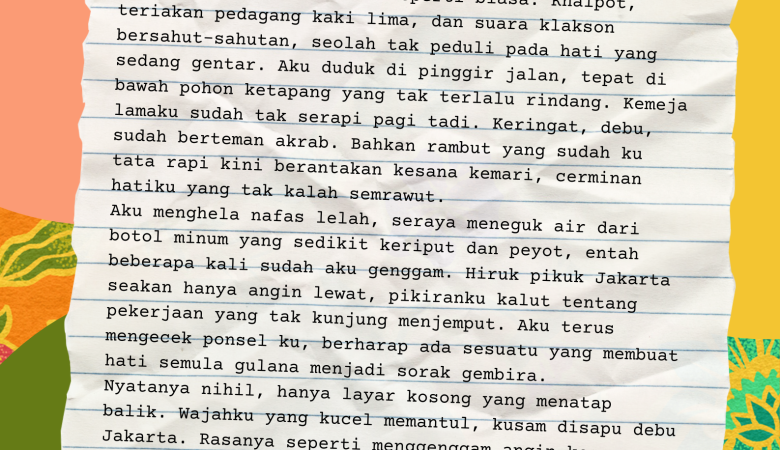
Lomba
Komentar (0)
Tinggalkan Jejak
Belum ada komentar saat ini.
Jadilah yang pertama memberikan apresiasi!
Kategori Berita
Punya Informasi Menarik?
Bagikan informasi beasiswa atau lowongan pekerjaan yang bermanfaat.
Hubungi Kami